
Banyak bicara dalam terminologi al-ihsan menuju penyucian diri disebut katsratul kalam, dan hal ini identik dengan perbuatan sia-sia lagi tercela di hadapan manusia bahkan Allah swt. Ini disebabkan karena banyak bicara dapat menghantarkan pada sesuatu yang diharamkan atau dibenci, contohnya adalah pembicaraan tentang kemaksiatan yang mengarah pada gosip, fitnah dan ghibah.
Ada beberapa petunjuk Rasulullah Muhammad saw yang melarang perbuatan banyak bicara ini, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani:
من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به
Artinya: “Barangsiapa yang banyak bicaranya maka banyak pula terpleset lisannya, barangsiapa yang banyak terpleset lisannya maka banyak pula dosanya, barangsiapa yang banyak dosanya maka neraka lebih utama untuknya.“
Terdapat pula riwayat yang tercatat oleh Imam al-Tirmidzi dan al-Baihaqi secara marfu’ ke Rasulullah Muhammad saw:
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى
Artinya: “Janganlah kalian banyak berbicara selain hanya untuk menyebut Allah, karen sungguh orang yang banyak berbicara selain untuk menyebut Allah maka hatinya akan mengeras, dan sungguh orang yang jauh dari manusia dan Allah adalah ia yang hatinya keras.”
Riwayat lainnya juga disampaikan dan tercatat oleh Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah secara marfu’ pula ke Rasulullah Muhammad saw:
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله
Artinya: “Semua ucapan anak Adam akan berdampak negatif baginya dan tidak akan berimplikasi positif, kecuali ucapan tersebut merupakan ajakan kepada orang lain agar berbuat yang ma’ruf atau larangan untuk berbuat kemungkaran atau senantiasa untuk berdzikir kepada Allah.“
Riwayat selanjutnya yang bersifat marfu’ hingga ke Rasulullah Muhammad saw, juga disampaikan oleh Abu al-Syaikh:
أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه
Artinya: “Banyak orang yang akhirnya mengumpulkan dosa hanya karena banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya baginya.“
Berdasar pada riwayat-riwayat di atas, Imam al-Kurdi (h.439) menasihati agar setiap muslim lebih banyak melakukan kontemplasi dan mengurangi banyak berbicara dengan memperbanyak diam, kecuali pembicaraan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya di dunia serta akhiratnya. Sebagai bahan penguat, diingatkanlah oleh Imam al-Kurdi dua ayat yang seringkali dilupakan:
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون
Artinya: “dan sungguh bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi pelerjaanmu, yang mulia (di sisi Allah) mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu).” [QS. al-Infithar: 10-11]
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
Artinya: “Ketika dua malaikat akan mencatat amal perbuatan seseorang, maka salah satunya duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” [QS. Qaf: 17-18]
Alangkah malunya diri ini, ketika ditunjukkan seluruh catatan amal-amal perbuatan, lalu nampak nyata amal perbuatan hasil dari pekerjaan lisan yang lebih didominasi oleh keburukan dan kemaksiatan, bukan perbuatan kebaikan yang disandari oleh kalimah lillahi ta’ala (karena dan untuk Allah semata).
Hendaknya diri ini mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh al-Rabi’ bin Khutsaim yang tidak pernah mengucapkan hal-hal yang buruk dan tidak berpaedah, karena setiap harinya senantiasa menyiapkan kertas dan pena di atas mejanya, lalu ia catat apa yang telah ia lakukan dan ucapkan, dan di sore harinya ia mengambil catatan tersebut sembari menghisab dirinya sebelum hisab dari Allah swt.
Ada kisah lainnya yang juga dapat dijadikan i’tibar (pelaran), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ibnu Ibi al-Dunya. Diceritakab bahwa suatu hari sekelompok orang bertamu kepada Ibrahim bin Adham. Ia menyambut tamu-tamu tersebut. Kemudian diketahuinya bahwa tamu-tamu yang datang ini adalah orang-orang yang mulia.
Berkatalah Ibrahim bin Adham kepada tamu-tamunya, “wasiatilah aku dengan wasiat yang dapat menyababkanku takut kepada Allah seperti takutnya kalian kepada-Nya.” Berkatalah salah datu tamunya tersebut, “Kami akan memberikan wasiat berupa tujuh perkara.“
من كثر كلامه فلاتطمع في يقظة قلبه
Artinya: “Siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap akan terjaga hatinya.“
من كثر كلامه فلا تطمع في أن تصل اليه الحكمة
Artinya: “Siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap mendapatkan hikmah.“
من كثر اختلاطه بالناس فلا تطمع في نواله حلاوة العبادة
Artinya: “Siapa yang kebanyakan bergaul dengan manusia, maka jangan harap memperoleh manisnya ibadah.“
من أفرط في حب الدنيا خيف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله
Artinya: “Siapa yang berlebihan dalam mencintai dunia, maka ditakutkan ia akan meninggal dengan su’ul khotimah, semoga kita mendapatkan perlindungan Allah.”
من كان جاهلا فلاترج فيه حياة القلب
Artinya: “Siapa yang bodoh, maka jangan harap hatinya hidup.“
من اختار صحبة الظلم فلا ترج فيه استقامة الدين
Artinya: “Siapa yang memilih bersahabat dengan orang yang zalim, maka jangan harap mendapatkan keutamaan istiqamah dalam beragama.”
Wasiat ketujuh atau terakhir adalah:
من طلب رضا الناس فقلما ينال رضاالله تعالى عنه
Artinya: “Orang yang hanya mencari ridha manusia, maka tidak akan sedikitpun ia memperoleh ridha Allah ta’ala.”
Melalui penjelasan-penjelasan di atas, yang di dasari oleh firman-firman Allah, hadits-hadits Rasulullah, serta kisah hikmah dan nasihat ahli hikmah, semoga kiat dapat memulai diri untuk menyedikitkan bicara, kecuali hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, baik kemanfaatn dunia maupun kemanfaatan akhirat. Semoga Allah swt senantiasa menjaga dan melindungi kita semua, amin ya Rabbal’alamin.
Wallahua’lam…



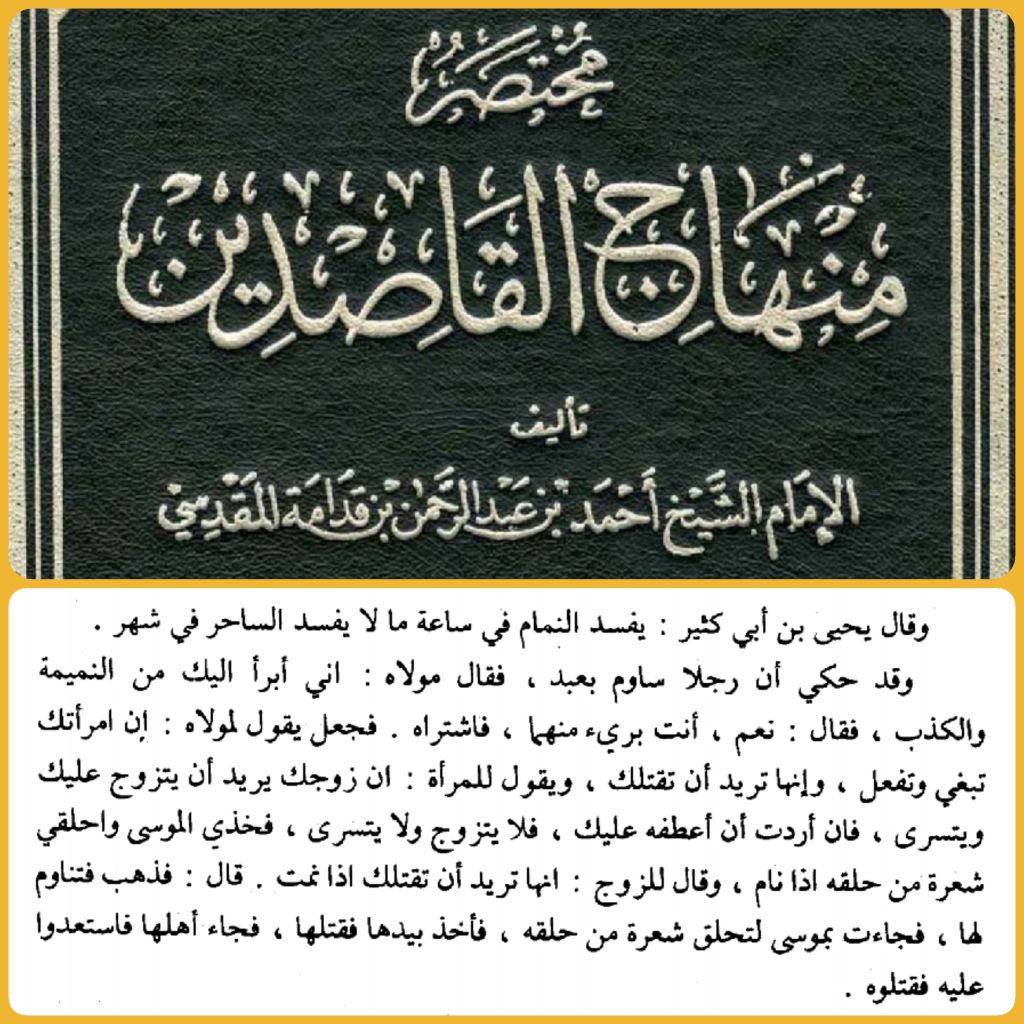






Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.